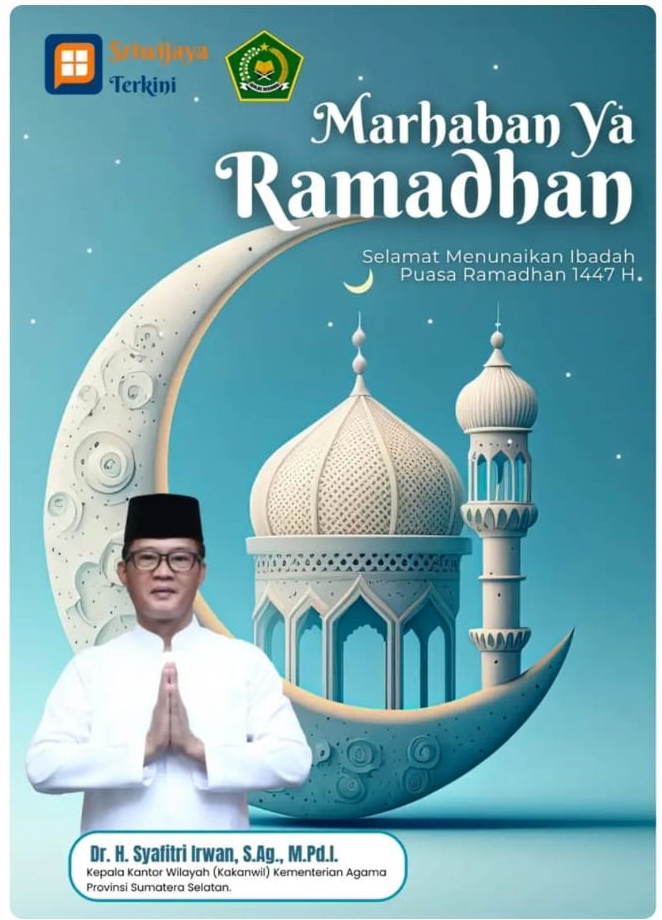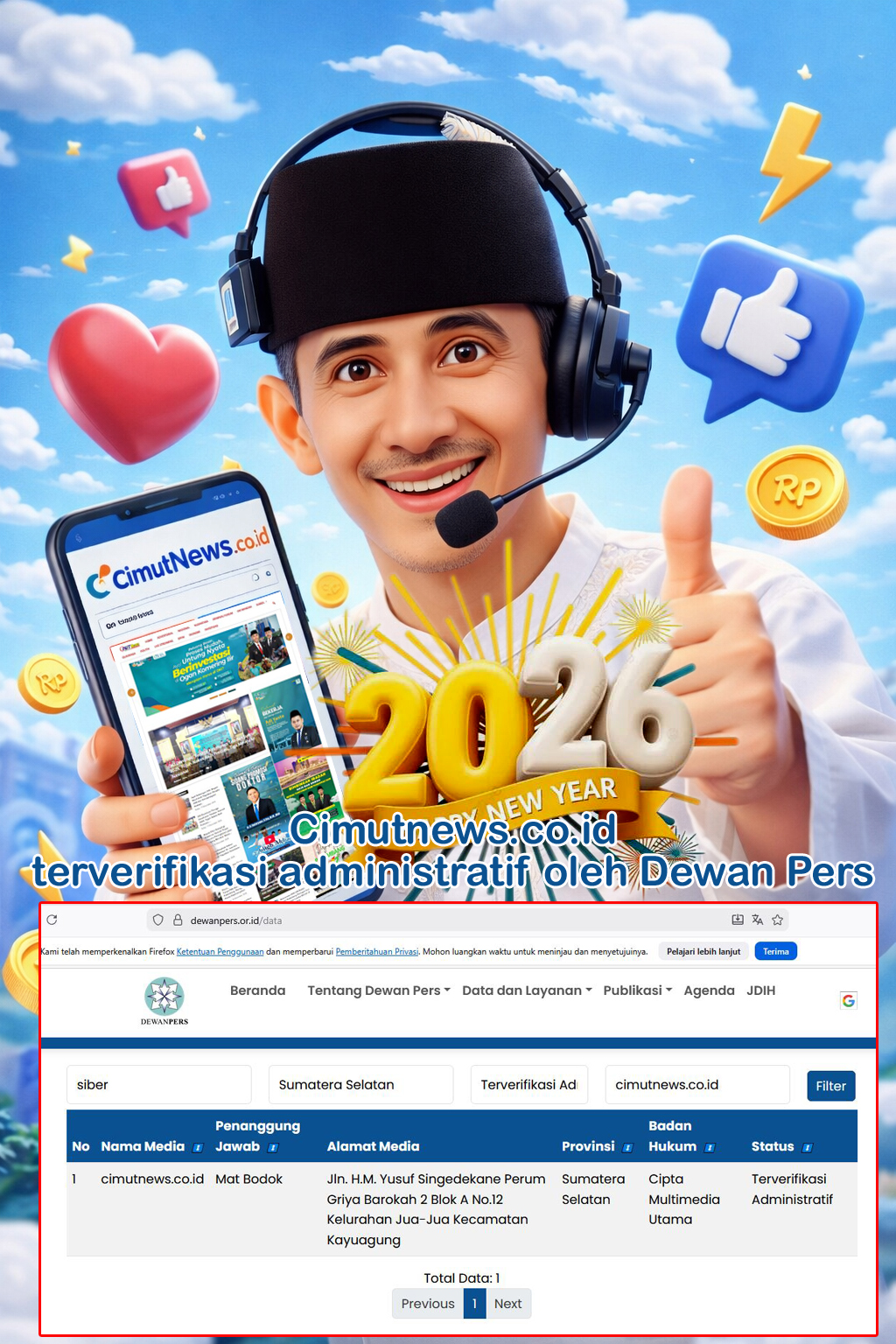Di sudut jalan Letnan Sayuti, Kayuagung, ada satu sosok yang dulunya menjadi pemandangan harian yang tak pernah absen: seorang pria tua bersahaja dengan gerobak es-nya. Bukan sekadar penjual es biasa, ia adalah bagian dari denyut kehidupan kota kecil ini. Ia adalah Abah Emon.
Tak ada yang menyangka, di antara gelas-gelas es yang dibagikannya setiap hari, ternyata nasib tragis telah mengintainya. Pada sore 11 Mei 2025, pisau kekerasan merobek tubuhnya yang renta — lima tusukan, lima luka, lima saksi bisu dari kegilaan yang tiba-tiba menyergap.
Abah Emon meninggal dunia di pagi buta, ketika fajar belum sepenuhnya menyingsing. Tubuhnya yang penuh luka tak sempat mengucap kata terakhir pada anaknya, Yayat. Tak sempat pamit pada gerobak kecilnya. Tak sempat menyapa langganannya. Ia pergi dalam diam, menyisakan gelombang duka yang menyapu satu kota.
Yang lebih memilukan, jasadnya sempat tertahan. Bukan oleh hukum, bukan oleh prosedur medis, tapi oleh tagihan rumah sakit — hampir Rp30 juta, nominal yang terlalu besar bagi keluarga kecil yang menggantungkan hidup dari hasil berjualan es. Dan dari sini, kita melihat betapa luka itu tak hanya datang dari pisau, tapi juga dari sistem.
Syukurlah, kemanusiaan belum benar-benar mati. dr. Oca, Direktur RSUD Kayuagung, turun tangan. Ia menjamin jenazah bisa dipulangkan ke kampung halaman, Kuningan — karena setiap manusia berhak pulang dalam damai, meski dalam sunyi.
Kita bertanya-tanya, kenapa? Mengapa pria tua yang bahkan tak pernah mencari masalah bisa menjadi sasaran kekerasan sebrutal itu? Apa motif pelaku? Gangguan jiwa? Dendam? Atau sekadar kekacauan sosial yang selama ini kita anggap biasa saja?
Kekerasan jalanan kini bukan lagi isu Jakarta atau kota besar. Ia menjalar, pelan-pelan, ke kota kecil seperti Kayuagung. Dan Abah Emon adalah korbannya. Bukan tokoh publik, bukan selebriti, bukan pejabat. Hanya seorang ayah. Seorang kakek. Seorang penjual es. Namun justru karena itulah, kisahnya begitu menyentuh dan menggugah.
Tempat Abah Emon biasa mangkal kini kosong. Tak ada lagi suara khas menawarkan es. Hanya ruang hampa, dan kesedihan yang menggantung. Tapi kita tak boleh membiarkan hampa itu menjadi sia-sia.
Kematian Abah Emon harus menjadi alarm sosial. Tentang pentingnya keamanan di ruang publik. Tentang kepekaan terhadap kesehatan mental masyarakat. Tentang sistem pelayanan kesehatan yang manusiawi. Tentang bagaimana orang-orang kecil sering kali menjadi korban—baik dari kekerasan, maupun dari sistem yang tak ramah.
Hari ini, kita mungkin masih bisa membeli es dari pedagang lain. Tapi rasa di hati kita takkan pernah sama. Karena di balik setiap gelas es yang Abah Emon jual, tersimpan peluh, cinta, dan harapan. Dan semua itu kini telah membeku.
Selamat jalan, Abah. Namamu kami kenang bukan karena siapa dirimu di atas panggung dunia, tapi karena ketulusanmu dalam menjalani hidup yang sederhana. Engkau telah pergi, tapi luka ini masih tertinggal. Semoga kisahmu membuka mata kita, dan mengetuk pintu-pintu hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan dan ketidakpedulian.
Kami tak hanya mendoakanmu, Abah. Kami juga bersumpah: tak akan diam.